JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan baru pemerintah terkait kenaikan tarif royalti nikel, yang dinilai membebani industri di tengah tekanan ekonomi global.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian ESDM.
PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025 dan mulai berlaku efektif 15 hari setelah pengundangan. Namun, pelaku industri mempertanyakan waktu dan dampaknya terhadap keberlangsungan sektor nikel nasional.
Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin, menyatakan bahwa kenaikan tarif royalti nikel saat ini sangat tidak tepat, mengingat harga nikel global tengah mengalami penurunan tajam akibat eskalasi geopolitik dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
“Kenaikan tarif royalti di tengah ketidakpastian ekonomi global berisiko memperburuk tekanan pada industri nikel nasional. Ini dapat mengurangi daya saing serta kontribusi sektor terhadap perekonomian,” tegas Meidy, dikutip Senin, (21/4/2025).
Tarif royalti terbaru yang diatur dalam beleid tersebut mencakup kenaikan royalti bijih nikel menjadi 14–19%, serta produk turunan seperti feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI) menjadi 5–7%.
APNI menilai tarif tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Meidy menyoroti sejumlah beban tambahan yang kini ditanggung pelaku usaha, antara lain: Kenaikan harga biosolar B40, Upah Minimum Regional (UMR) naik 6,5%, PPN 12%, Kewajiban devisa hasil ekspor (DHE) 100% selama 12 bulan, Biaya pembangunan smelter yang tinggi, mencapai US$1,5–2 miliar per unit, Kewajiban reklamasi, PNBP, PPM, hingga pajak global (global minimum tax 15%).
“Beban kumulatif ini menekan margin produksi secara signifikan, bahkan bisa mengurangi potensi penerimaan negara dari produk smelter yang tidak lagi kompetitif di pasar global,” imbuh Meidy.
APNI Tawarkan Solusi: Revisi Formula Harga Patokan Mineral (HPM)
Sebagai solusi, APNI mengusulkan revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) agar lebih mencerminkan nilai keekonomian bijih nikel.
Menurut mereka, HPM saat ini terlalu rendah dibanding indeks internasional seperti Shanghai Metals Market (SMM), yang dapat menyebabkan potensi kerugian nilai pasar hingga US$6,3 miliar dalam dua tahun terakhir.
Usulan revisi mencakup:
– Menambahkan nilai keekonomian kandungan besi (saprolit) dan kobalt (limonit) yang belum termonetisasi
– Meningkatkan HPM hingga lebih dari 100% tergantung kualitas bijih
– Mengganti satuan transaksi dari US$/dmt ke US$/ton nikel murni atau US$/nikel unit agar sejalan dengan praktik internasional
– Evaluasi ulang corrective factor (CF) yang dinilai sudah tidak relevan untuk produk feronikel
Revisi ini, menurut APNI, berpotensi menghasilkan manfaat jangka panjang seperti: Peningkatan penerimaan negara tanpa perlu menaikkan tarif royalti, Margin usaha yang lebih sehat bagi pelaku industri untuk mendukung eksplorasi dan keberlanjutan, Peningkatan cadangan melalui penurunan cut-off grade, Kenaikan nilai ekspor produk hilir, Insentif pengembangan teknologi ekstraksi mineral ikutan seperti besi dan kobalt.
Meski keberatan dengan kebijakan baru, APNI tetap mendukung agenda hilirisasi nasional. Mereka berharap pemerintah bersedia membuka ruang dialog untuk memastikan implementasi PP No. 19/2025 dilakukan dengan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan.
“Kami mendorong agar kebijakan fiskal di sektor minerba diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Meidy. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
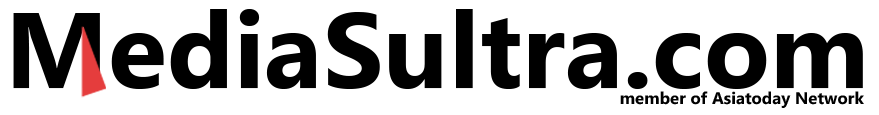
















Discussion about this post